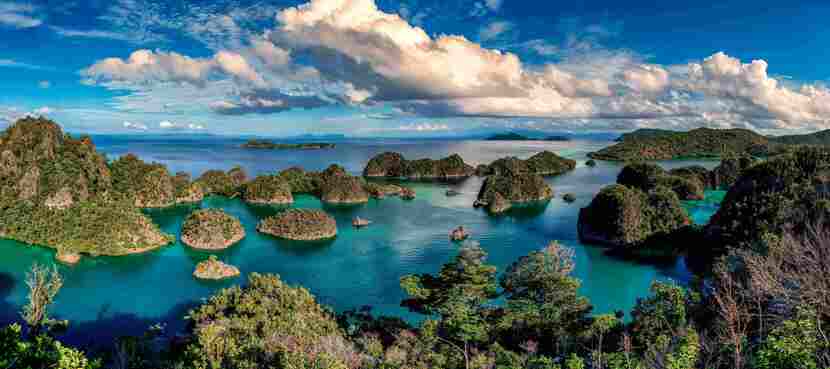Indonesia dengan keberagaman masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan agama. Setiap adat istiadat, ritual, dan karya seni mencerminkan semangat hidup berdampingan, menghargai perbedaan, serta memperkuat persatuan. Dari keberagaman itu melahirkan ragam kebudayaan atau tradisi memiliki banyak makna, di antaranya makna perdamaian antar sesama.
Sobat Pesona, berikut ini beberapa budaya di Indonesia yang memiliki makna perdamaian:
1. Tradisi Ngejot
Foto: piaagungbali.com
Tradisi Ngejot di Bali merupakan salah satu bentuk kerukunan antar umat beragama. Secara harfiah Ngejot berarti memberi, sehingga tradisi ini merupakan wujud nyata dari semangat berbagi dan pertemanan di antara sesama. Ngejot dilaksanakan menjelang hari-hari raya keagamaan seperti Galungan, Kuningan, Nyepi, Idul Fitri, Idul Adha, atau Natal.
Ngejot juga dapat dilihat sebagai ungkapan rasa terima kasih. Dalam upacara-upacara seperti Yadnya, di mana keluarga akan memberikan pengwales (balasan) kepada mereka yang telah membantu. Tradisi Ngejot ini menjadi simbol ikatan kekeluargaan, terutama saat upacara Galungan di mana masyarakat saling berbagi makanan.
Filosofi yang melandasi hubungan sosial masyarakat Bali, berakar pada ajaran Tri Hita Karana. Ajaran ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam, sesama manusia, dan Tuhan. Melalui prinsip ini, masyarakat Bali berhasil menjaga hubungan sosial yang rukun dan harmonis antar umat beragama.
Dengan adanya tradisi Ngejot, masyarakat Bali berhasil mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat, seperti kebersamaan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama.
2. Pela Gandong
Foto: kawulamahardhika.wordpress.com
Maluku juga memiliki warisan budaya yang kaya salah satunya adalah tradisi Pela Gandong. Tradisi ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku dan hubungan sosial masyarakat Maluku.
Pela Gandong merupakan istilah yang menggambarkan ikatan persaudaraan antara dua negeri atau desa yang saling menerima satu sama lain sebagai saudara. Kata "Pela" berarti ikatan persaudaraan, sedangkan "Gandong" memiliki makna saudara, sehingga Pela Gandong dapat diartikan sebagai persatuan yang didasari oleh hubungan persaudaraan.
Pada masa penjajahan belanda, Pela Gandong di Maluku bermula dari hubungan antar 2 negeri yang berbeda agama, yaitu Islam dan Kristen.
Tahun 1921, kedua negeri tersebut berkolaborasi dalam sebuah perlombaan perahu belang yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda. Tim gabungan dari Kailolo dan Tihulale berhasil memenangkan perlombaan tersebut, sehingga sejak itu hubungan persaudaraan antara kedua negeri terjalin dengan hangat.
Kedekatan ini semakin terlihat ketika masyarakat Kailolo membangun Masjid Nan Datu. Mereka mengundang warga Tihulale, yang datang membawa kayu dan papan untuk membantu pembangunan masjid.
Sebagai bentuk balas budi, ketika Tihulale membangun Gereja Beth Eden, warga Kailolo memberikan bantuan berupa gerabah. Pertukaran ini menegaskan kuatnya ikatan Pela Gandong di antara kedua negeri.
Budaya Pela Gandong tidak hanya berfungsi sebagai ikatan sosial tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kerukunan dan harmoni di antara masyarakat yang berbeda agama, ras, dan suku. Tradisi ini menjadi landasan penting dalam menjaga kedamaian dan kebersamaan di Maluku, terutama di tengah keberagaman yang ada. Budaya ini terus dilestarikan dan diperkuat guna memastikan kehidupan yang rukun dan damai di wilayah tersebut.
Nilai-nilai Pela Gandong terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Maluku. Salah satu wujud nyatanya adalah melalui konsep "Ale Rasa Beta Rasa," yang memiliki arti "apa yang kamu rasakan, aku juga rasakan." Ungkapan ini mencerminkan empati, kebersamaan, dan cinta kasih di antara masyarakat Maluku, meskipun mereka berbeda kampung, agama, status sosial, atau gender.
3. Bakar Batu
Di Lembah Baliem, Papua, terdapat tradisi Bakar Batu. Upacara Bakar Batu juga dikenal sebagai Barapen. Hingga kini, tradisi Bakar Batu merupakan salah satu warisan budaya yang dijaga oleh berbagai suku di pegunungan Papua, termasuk Suku Dani di Lembah Baliem. Tradisi ini diisi dengan memasak bersama secara massal menggunakan batu panas sebagai media utamanya.
Namun, Bakar Batu bukan sekadar acara memasak, tetapi sebuah upacara penuh makna yang mencerminkan rasa syukur dan kebersamaan. Upacara ini ditujukan sebagai bentuk syukur kepada Sang pemberi kehidupan atas berkat yang telah diberikan. Selain itu, Bakar Batu juga sebagai ajang mempererat silaturahmi antar warga suku serta memperkuat persahabatan di antara berbagai etnis di Papua.
Di masa yang lalu, Bakar Batu sering dilakukan sebagai persiapan untuk perang suku atau sebagai perayaan atas kemenangan atau perdamaian yang berhasil dicapai setelah konflik antarsuku. Namun saat ini, Bakar Batu juga diadakan saat menyambut momen-momen penting seperti perayaan besar, penyambutan tamu, atau sebagai ungkapan kegembiraan setelah tercapainya kesepakatan damai.
Untuk persiapan prosesi Bakar Batu, warga mengumpulkan batu-batu yang kemudian dipanaskan hingga membara. Batu panas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang telah disiapkan.
Di atas batu, diletakkan lapisan daun sebagai alas sebelum daging dan ubi-ubian dimasukkan ke dalamnya. Setelah itu, bahan makanan kembali ditutupi dengan dedaunan sebelum lapisan batu panas ditambahkan di atasnya, dan akhirnya proses pembakaran dimulai.
Selama menunggu makanan matang, warga suku juga menggelar kegiatan lain, seperti tarian adat massal atau forum diskusi antara kepala suku dan warga. Setelah beberapa jam, makanan yang sudah matang diambil dari lubang dan dihidangkan di atas hamparan daun pisang untuk dinikmati bersama.
Tradisi ini memiliki nilai filosofis yang mencerminkan kesederhanaan, kebersamaan, dan rasa syukur masyarakat adat Papua. Tradisi ini menjadi bukti bagaimana masyarakat Papua menghormati alam dan sesama, menjaga kerukunan, serta merayakan kebersamaan dalam setiap momen penting kehidupan.
4. Tudang Sipulung
Foto: rakyatku.com
Tudang Sipulung juga dikenal sebagai Empo Sipitangarri dalam bahasa Makassar. Tradisi ini merupakan khas masyarakat Bugis dan Makassar, Sulawesi Selatan yang mengedepankan prinsip musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
Tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu, berfungsi sebagai wadah untuk berkumpul dan berdiskusi demi mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
Secara harfiah, kata "Tudang" dalam bahasa Bugis berarti duduk, sedangkan "Sipulung" berarti berkumpul. Jadi Sobat Pesona, Tudang Sipulung dapat diartikan sebagai duduk berkumpul untuk membahas hal-hal penting dalam musyawarah.
Sedangkan dalam bahasa Makassar, Empo berarti duduk dan Sipitangarri mengandung makna saling memberi usul dan saran. Baik Tudang Sipulung maupun Empo Sipitangarri menggambarkan proses interaksi antara masyarakat dan pemimpin untuk mencari solusi bersama.
Tudang Sipulung sudah ada sejak abad ke-13 hingga ke-14, jauh sebelum Islam masuk ke wilayah Sulawesi Selatan. Tradisi ini tercatat dalam Lontara Bugis, salah satu naskah kuno yang memuat catatan sejarah dan adat istiadat masyarakat Bugis. Konsep ini diperkenalkan oleh La Pagala, yang lebih dikenal sebagai Nenek Mallomo, seorang cendekiawan dan pemimpin bijak dari masa lampau.
Di sisi lain, dalam tradisi masyarakat Makassar, Tumanurung, raja pertama Makassar, juga mengadakan Empo Sipitangarri dengan para pemimpin adat untuk merumuskan perjanjian tentang sistem pemerintahan. Tradisi ini menetapkan hak, wewenang, dan tanggung jawab antara rakyat dan pemimpin, sehingga memperjelas bahwa rakyat memegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara.
Tudang Sipulung dilaksanakan secara terbuka dan demokratis, baik di lingkungan keluarga maupun dalam skala yang lebih besar, seperti antar desa atau kerajaan. Pada tingkat informal, musyawarah ini biasanya dipimpin oleh Arung Matoa (tetua adat), sedangkan pada tingkat formal, musyawarah dipimpin oleh Tudang Wanua (kepala desa atau raja). Para peserta musyawarah, termasuk pakketenni ade' (penghulu adat), berkewajiban mengemukakan pendapatnya, dan setiap pendapat dihargai dan dipertimbangkan.
Tradisi Tudang Sipulung telah diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2016. Pengakuan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kearifan lokal masyarakat Bugis dan Makassar yang telah menjaga tradisi musyawarah sebagai bagian penting dari kehidupan sosial.
Pesan perdamaian yang mendasari di beberapa budaya ataupun tradisi di berbagai wilayah tersebut, menjadikan Indonesia sebagai simbol toleransi dan persatuan di tengah perbedaan, sesuai dengan peringatan World Tourism Day 2024 yang lalu, yang mengangkat tema Tourism and Peace dengan subtema Promoting World Peace Through Community Engagement in Sustainable Tourism. Kurang lebih pesannya adalah pariwisata juga dapat menjadi alat yang ampuh untuk menumbuhkan pemahaman internasional, pertukaran budaya, dan perdamaian global.
Semoga mulai dari diri kamu, mulai dari keindahan wisata, dan mulai dari ragam budaya Indonesia, bisa menjadi percikan perdamaian untuk dunia ya, Sob. Ikuti informasi pariwisata dan budaya #DiIndonesiaAja dengan follow Instagram @pesona.indonesia.